Homo Significans: Basis Konsumerisme Postmodern
Manusia ialah makhluk yang mempunyai berbagai macam perilaku dan budaya, baik bersifat primordial maupun hasil pembentukan suatu karakter dari sebuah lingkungan hidupnya. Perilaku dan budaya menjadi ciri khas manusia, sebab hanya manusialah makhluk di dunia yang memilikinya. Alasannya ialah bahwa perilaku dan budaya berkaitan erat dengan kesadaran, yang hanya dimiliki oleh manusia.
Seiring perkembangan zaman, perilaku dan budaya manusia terus mengalami dinamika yang sampai saat ini belum mengalami produk final. Salah satu perilaku dan budaya yang berkembang di masyarakat global ialah budaya konsumerisme.
Permasalahan mengenai budaya konsumerisme ini banyak diperbincangkan, namun tak kunjung usai. Inilah mengapa penulis tertarik untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan budaya konsumerisme tersebut, terkait dengan salah satu sifat manusia, yaitu homo significans.
Definisi Konsumerisme
Ada beberapa konseptualisasi dalam istilah konsumsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumsi diartikan sebagai perilaku yang bergantung pada hasil produksi pihak lain (hanya memakai dan tidak menghasilkan sendiri).
Yasraf memaknai konsumsi sebagai sebuah proses objektifikasi, yaitu proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-ojek sebagai medianya (Yasraf, 2004), maksudnya lebih kepada bagaimana kita memahami dan mengkonseptualisasikan diri maupun realitas di sekitar kita melalui objek-objek material. Di sini terjadi proses menciptakan nilai-nilai melalui objek-objek dan kemudian memberikan pengakuan serta penginternalisasian nilai-nilai tersebut.
Definisi tersebut memberi frame bagi kita dalam memahami alasan mengapa orang terus-menerus berkonsumsi. Objek-objek konsumsi telah menjadi bagian yang internal pada kedirian seseorang, sehingga sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pemahaman konsep diri.
Sebagai ilustrasi misalnya, banyak remaja merasa “gaul” jika mereka mengenakan celana jeans. Pakaian yang merupakan objek konsumsi, menjadi penanda identitas mereka dibanding karakter psikis, emosional, ataupun penanda fisik pada tubuh mereka (Yasraf, 2004).
Konsumerisme menurut KBBI ialah suatu paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya; gaya hidup yang tidak hemat.
Konsumerisme sebenarnya sama dengan perilaku konsumsi, hanya saja dalam tahap konsumerisme, seseorang telah mengalami evolusi konsumsi. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi melakukan aktifitas konsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya, namun lebih bersifat radikal, artinya cenderung kepada pemuasan sifat keserakahan dari manusia.
Homo Significans
Tanda merupakan salah satu kebutuhan lahir batin manusia untuk memahami dinamika kehidupannya. Peran tanda dalam kehidupan manusia bahkan setara dengan kebutuhan primer seperti: makan dan minum. Kekurangan makan dan minum menjadikan manusia menderita secara fisik, namun kemiskinan pemahaman akan tanda menjadikan manusia kehilangan momen penting dalam hidupnya, bahkan derita batin yang berkepanjangan (Muntasyir, 2006).
Manusia adalah makhluk hidup pembuat tanda (Homo significan) yang mencoba mengidentifikasikan objek di luar dirinya secara logis-rasional. Realitas hidup merupakan rangkaian enigmatic yang menuntut pencarian jawaban, yang disebut kebenaran.
Karena itulah diperlukan penyelidikan sebagai sebuah kegiatan mencari petunjuk, bukti, tanda (signs), serta melihat logika, relasi, kausalitas di antara semuanya untuk memperoleh kesimpulan akhir. Tanda melibatkan aktivitas mental dan pikiran manusia, sehingga horizon manusia mengalami pengembangan yang pesat tergantung pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri dalam memahami dan memaknai tanda.
Penanda (signifier) sebagai sesuatu yang konkret berperan sebagai kendaraan tanda di satu pihak dan petanda (signified) sebagai bentuk pemahaman makna atau konsep di pihak lain, saling berelasi dalam kehidupan budaya manusia. Aktivitas mental dan pikiran merupakan wahana pengembangan kebudayaan, sehingga pemahaman atas kehidupan menjadi lebih kompleks (Muntasyir, 2006).
Pola Konsumerisme Manusia Kini
Dalam ciri masyarakat postmodern, tanda-tanda pada objek konsumsi pada kenyataannya, justru cenderung digunakan untuk menandai relasi-relasi sosial. Saat ini, objek konsumsi mampu menentukan prestasi, status, dan simbol-simbol sosial tertentu bagi pemakainya.
Objek juga mampu membentuk perbedaan-perbedaan sosial dan menaturalisasikannya melalui perbedaan-perbedaan pada tingkat pertandaan. Itulah mengapa orang cenderung menilai dan mengenali orang dari penampilan luar (eksternal), apa yang dikenakannya, aksesorisnya, dan sebagainya. Barang-barang bermerk menunjukkan nilai sosial yang tinggi. Pada barang-barang tersebut, tertempel nilai eksklusifitas.
Memang kenyataannya bahwa konsumsi sebagai satu sistem diferensiasi, sistem pembentukan perbedaan-perbedaan status, simbol (signs), dan prestasi sosial telah menandai pola sosial masyarakat konsumer. Dalam masyarakat konsumerisme, masyarakat hidup di suatu bentuk relasi subjek-subjek yang baru, yatu relasi konsumerisme.
Dalam masyarakat konsumer, objek-objek konsumsi dipandang sebagai ekspresi diri atau eksternalisasi para konsumer (bukan melalui kegiatan penciptaan), dan sekaligus sebagai internalisasi nilai-nilai sosial-budaya yang terkandung di dalamnya. Tidak heran apabila saat ini banyak sekali kelompok-kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan konsumsi terhadap produk tertentu.
Misalnya kelompok Grup Motor “Harley Davidson”, dan sebagainya. Komunitas tersebut terbentuk sebagai upaya pembentukan differensiasi dan prestasi. Komunitas semacam itu menyetarakan eksklusifitas mereka dengan merek-merek tersebut.
Maka kini, adalah suatu hal wajar apabila manusia sering mendengar orang-orang beterbangan kesana-kemari, berpindah tempat dari satu benua ke benua yang lainnya hanya untuk berbelanja atau shopping. Adalah hal yang wajar pula ketika masyarakat menyaksikan para artis pergi ke luar negeri hanya untuk sekedar membeli baju atau tas.
Masyarakat kini menginternalisasi kegiatan konsumsi dan kemudian mengubah pengalaman ini ke dalam semua aktifitas manusia lainnya dan ke dalam aspek-aspek eksistensi sosial manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa konsumsi telah terkonstruksi dalam rasionalitas masyarakat global dunia sehingga konseptualisasi masyarakat mengenai diri dan dunia dipengaruhi atau dibentuk oleh konsumsi (Guntur, 2012).
Konsumerisme pada masa sekarang telah menjadi ideologi baru. Ideologi tersebut secara aktif memberi makna tentang hidup melalui mengkonsumsi material. Bahkan ideologi tersebut mendasari rasionalitas masyarakat kita sekarang, sehingga segala sesuatu yang dipikirkan atau dilakukan diukur dengan perhitungan material. Ideologi tersebut jugalah yang membuat orang tiada lelah bekerja keras mengumpulkan modal untuk dapat melakukan konsumsi.
Berkaitan dengan budaya konsumerisme, sifat homo significan dalam diri manusia sangat berpengaruh. Salah satu analisis terkait dengan hal tersebut ialah analisis Baudrillard mengenai budaya konsumerisme masyarakat posmodern. Dalam pemikiran Baudrillard, yaitu bahwa konsumsi membutuhkan manipulasi simbol-simbol secara aktif.
Bahkan menurut Baudrillard, yang dikonsumsi bukan lagi use atau exchange value, melainkan symbolic value. Maksudnya ialah orang tidak lagi mengkonsumsi objek berdasarkan nilai kegunaan atau nilai tukarnya, melainkan karena nilai simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi (Baudrillard, 2004).
Konsumerisme juga terjadi seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perubahan dan inovasi, sebagai respon terhadap pengulangan yang sangat cepat dari hal-hal yang lama atau pencarian terhadap hal yang baru: produk baru, pengalaman baru, dan citra baru.
Apa yang penting dari analisa ini adalah adanya perubahan bertahap pada abad ke-20 dari sentralitas produksi barang-barang, menjadi kepentingan politis dan budaya dari produksi kebutuhan.
Pandangan Baudrillard memberikan analisis yang original tentang masyarakat konsumen, dan juga dapat menjelaskan bagaimana struktur komunikasi dan sistem tanda mampu mempertahankan eksistensi masyarakat konsumen tersebut.
Analisa Baudrillard tentang masyarakat konsumsi disarikan melalui analisa dari disiplin semiotika, psikoanalisa, dan ekonomi politik dalam produksi tanda. Menurut Baudrillard, sistem komunikasi berperan sangat penting dalam masyarakat konsumen. Terutama menyangkut produksi tanda.
Menurut Baudrillard, modernisme berkaitan dengan proses produksi objek, sedangkan posmodernisme lebih berkonsentrasi terhadap simulasi dan produksi tanda. Bagi Baudrillard, yang menandai transisi konsumsi tradisional menjadi konsumerisme adalah pengorganisasian konsumsi ke dalam suatu sistem tanda (Baudrillard, 2004).
_____
Riemas Ginong Pratidina, Alumni Fak. Filsafat UGM dan Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
_____
Pustaka Acuan
Amir Piliang, Yasraf. 2004. Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Bandung: Jalasutra
Baudrillard, Jean P.. 2004. Consumer Society (terjemahan Wahyunto). Yogyakarta: Kreasi Wacana
Muntasyir, Rizal. 2006. Notonagoro Sebagai Homo Significans Atas Ideologi Pancasila dalam Jurnal Filsafat “Wisdom”. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
Rahmatullah, Guntur. 2012. Konsumerisme, Budaya atau Gejala?. Tangerang: Margin Kiri
Bagikan artikel ini :

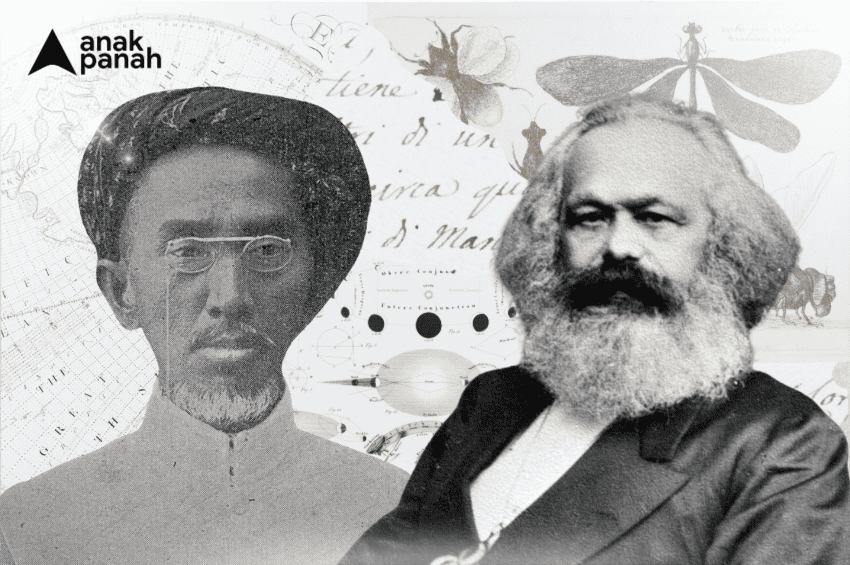

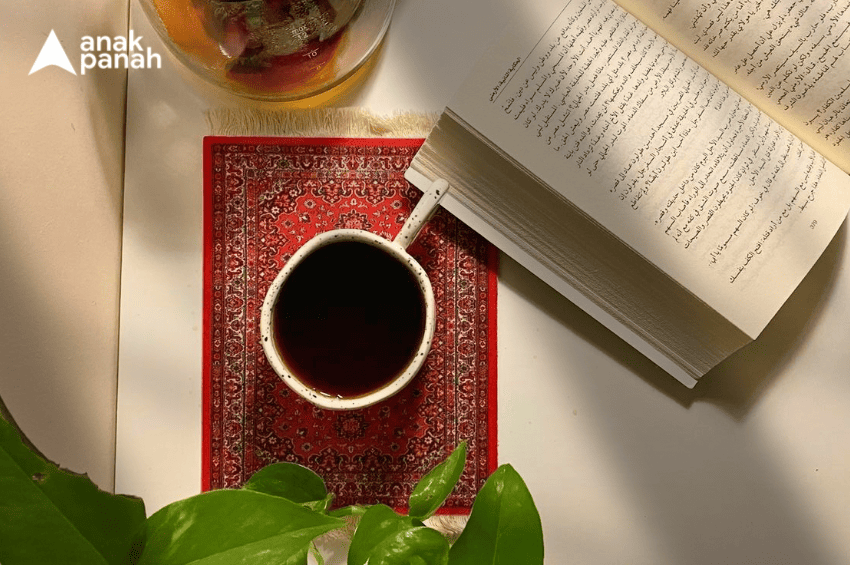




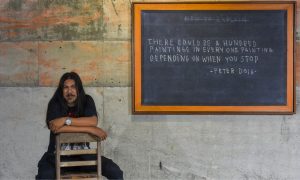

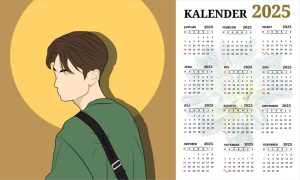


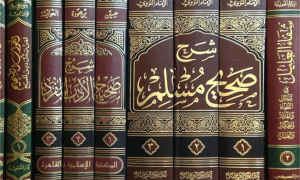
Post Comment