Diskursus Profetik Dulu dan Kini
Diskursus profetik awal mulanya muncul dari kajian filsafat, yaitu filsafat profetik. Di mana sejarah mencatat terjadinya dinamika dalam pencarian epistemologis yang sesuai bagi manusia, guna mengungkap fenomena kehidupan sampai pada intinya. Bukan hanya pengungkapan dengan nominal atau “perasaan” masing-masing individu, melainkan makna dari berbagai peristiwa yang ada kaitannya dengan pencipta peristiwa itu sendiri, yakni Tuhan Semesta Alam.
Periode Awal
Secara historis, fisafat profetik diperbincangkan intensif oleh Ibn Arabi (1165-1241) dan Suhrawardi (1155-1191), yang secara garis besar mengkritik filsafat dari peradaban Yunani sampai dengan masa modern. Di mana perbincangan filsafat masa itu hanya berkutat daripada batas manusia dan alam saja, tidak ada produk pemikiran yang berkaitan akan hubungannya dengan Tuhan.
Untuk Ibn Arabi sendiri, yang lebih dikenal sebagai Syaikh al-Akbar Ibn al-‘Arabi (sebagai catatan, di Indonesia beliau dipanggil dengan sebutan Ibn ‘Arabi [tanpa prefix “AL”] untuk membedakannya dengan Ibn al-‘Arabi pengarang tafsir Ahkam Al-Qur’an).
Dalam beberapa tulisan, produk pemikiran Ibn Arabi secara garis besar menjelaskan dua jenis ilmu pengetahuan, yakni ilmu yang dapat diperoleh melalui kekuatan rasional, dan pengetahuan yang diperoleh melalui praktek-praktek gnosis spiritual dan pengungkapan diri (tajalli) Allah.
Untuk mengungkapkan adanya hubungan dengan Allah, Ibn Arabi selalu terikat dengan 3 metafisika dasar yang telah dibangunnya, yakni adanya persatuan wujud (wahdat al-Wujud), manusia sempurna (al-Insan al-Kamil), dan dunia imaginal (al-A’lam al-Khayyal).
Selanjutnya, Al-Suhrawardi sebagai seorang tokoh sufi dengan nama lengkapnya Syihabuddin Yahya bin Hafasy bin Amirek Suhrawardi yang diberi gelar dengan al-Maqtul (artinya yang dibunuh).
Inti pemikiran beliau selalu terkait dengan konsep Isyraqy (sebuah konsep tentang term “penyinaran” dari “Nur al-Anwar”) dan Hakikat Tuhan (Cahaya dari segala Cahaya), kedua hal tersebut merupakan wujud realitas yang bersifat absolut dan tidak terbatas, karena tidak terbatas sehingga atas kehendak-Nya, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini beserta isinya tercipta.
Periode Modern
Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran yang ada tersebut kemudian dielaborasi dengan beberapa teori yang diadopsi oleh Muhammad Iqbal sebagai filosof dari benua India pada abad 20, dan diulas pula oleh Roger Garaudy sebagai guru besar filsafat Universitas Politier di Perancis, filosof perancis yang jadi Muslim, kita belajar tentang filsafat profetik.
Dalam kesimpulannya, filsafat Barat dari Yunani sampai dengan modern telah gagal mengantarkan manusia dalam memahami realitas secara utuh, berlainan dengan filsafat Islam, yang menurutnya Al-Qur’an dapat mengantarkan manusia kepada alam ketuhanan dan kenabian.
Menurut Muhammad Iqbal sendiri, ilmu pengetahuan bersumber dari tiga hal, yakni afaq (dunia), anfus (diri / ego), dan sejarah. Ketiga sumber pengetahuan ini didasarkan pada konsep khudi (individualitas / jiwa), yang untuk mencapai pengetahuan memerlukan ‘isyq (cinta) yang berkarakter dinamis. ‘Isyq tersendiri merupakan instrumen penggerak menuju perubahan pengetahuan menuju kesempurnaan hingga mencapai kebenaran hakiki (ma’rifat-Allah)
Periode Post-Modern
Di Indonesia sendiri, muncul seorang pemikir, sejarawan, dan seorang ilmuwan sosial yang pemikirannya diilhami dari Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy yakni Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetiknya. Roger Garaudy merasa ketidakpuasan terhadap filsafat barat yang notabene terombang-ambing antara dua kubu, idealis dan materialis, tanpa kesudahan.
Menurutnya, filsafat barat lahir dari pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan, sedangkan Ia menyarankan bagaimana wahyu itu dimungkinkan, karena selama ini wahyu dikesampingkan dari realitas.
Kuntowijoyo dalam melihat polemik tersebut menawarkan sebuah teori sebagai upaya pemecahan masalah dengan menginterpretasi dari Q.S. Ali-‘Imran ayat 110, yang memuat tiga pilar yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, dimana ketiga pilar tersebut dijadikannya sebagai epistemologi dalam teori ilmu sosial profetiknya (ISP).
Lebih lanjut Moh. Roqib dalam pemikiran profetiknya, memunculkan gagasan yang arahnya ke dunia pendidikan, dan menjadi sebuah teori baru berupa pendidikan profetik. Rupanya Moh. Roqib ini terilhami dari pemikiran tokoh sebelumnya yang menyinggung tentang profetik. Di mana tiga pilar ilmu sosial profetiknya Kuntowijoyo (humanisasi, liberasi, dan transendensi) dijadikan sebagai bahan pengembangan dalam pendidikan profetiknya.
Menurutnya, ketiga pilar tersebut haruslah berdialog dengan budaya lokal setempat, terutama budaya yang terbingkai dalam nilai akhlaqul karimah, dengan mempertahankan yang positif dan mengambil secara kreatif hal baru yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan agar terciptanya khairu ummah.
Bagikan artikel ini :
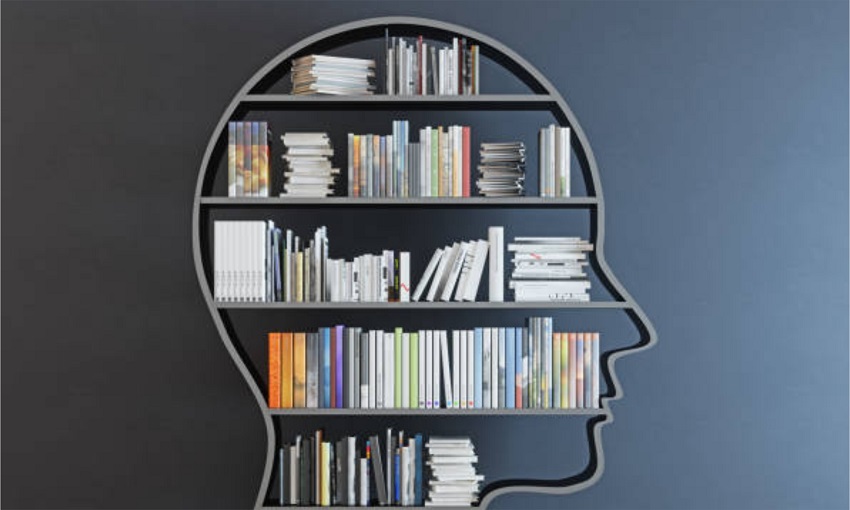






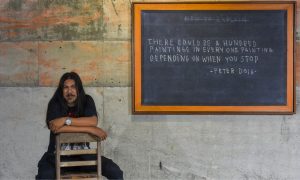

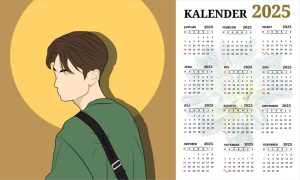


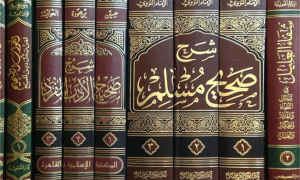
Post Comment