Perempuan Afghanistan dalam Novel A Thousand Splendid Suns
Terbersit rasa hampa dan kekosongan yang sulit diungkapkan setelah menuntaskan novel A Thousand Splendid Suns. Karya monumental Khaled Hosseini yang terbit pada 2007 ini kembali menggugah ruang kesadaran. Selain itu, novel ini mengungkap dengan telanjang realitas pahit yang dialami perempuan Afghanistan—sebuah pengalaman literer yang meninggalkan kesan mendalam sekaligus refleksi yang panjang.
Novel ini menyusul kesuksesan besar karya debut Hosseini pada 2003, The Kite Runner, yang lebih dulu singgah di hati pembaca lewat kisah persahabatan dan penebusan. Namun, Hosseini menyebut A Thousand Splendid Suns sebagai kisah ibu dan anak. Ini berbeda dengan The Kite Runner yang ia anggap sebagai kisah ayah dan anak.
Perempuan Afghanistan
Dalam A Thousand Splendid Suns (2007), Hosseini kembali menghadirkan potret getir kehidupan di Afghanistan, khususnya perempuan. Di tengah derasnya kekerasan struktural, perang berkepanjangan, dan dominasi patriarki, perempuan hadir sebagai pihak yang paling rentan. Novel ini tidak berhenti sebagai kisah perempuan yang tertindas—Mariam dan Laila. Sebaliknya, ia menjadi alegori tentang ketahanan dan kebangkitan perempuan dalam sistem yang membunuh habis-habisan.
Hosseini membawa pembaca menempuh lanskap sejarah yang terus bergejolak, dari masa pemerintahan monarki hingga rezim Taliban. Dalam konteks ini, perempuan sering kehilangan agensi sosial, politik, bahkan atas tubuhnya sendiri.
Patriarki
Meski patriarki bekerja hampir di setiap jengkal kehidupan, melalui Mariam dan Laila Hosseini menyoroti bagaimana patriarki membunuh mereka dalam dua lapis: publik dan domestik.
Pertama, patriarki hadir melalui pernikahan yang tidak pernah diinginkan. Mariam dipaksa menerima kenyataan seolah itulah jalannya. Sementara itu, Rasheed—suami Laila—menjadi representasi patriarki domestik: mengatur pakaian, membatasi aktivitas, hingga menentukan ruang gerak perempuan.
Lebih lanjut, kekerasan hadir sebagai bentuk kontrol. Di sisi lain, hukum sosial dan rezim politik kala itu ikut berperan sebagai patriarki publik. Mereka membenarkan kekerasan dengan dalih moral dan tafsir agama.
Baca juga resensi lainnya di kategori Resensi AnakPanah.id.
Memposisikan Perempuan
Kutipan, “Like a compass needle that points north, a man’s accusing finger always finds a woman” menjadi sorotan penting. Dengan kata lain, dalam budaya patriarkal, kesalahan sosial sering kali diarahkan kepada perempuan.
Pada titik ini, Hosseini menegaskan bahwa posisi perempuan didefinisikan bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh lingkungan, laki-laki, serta kekuasaan yang mengitari. Bahkan, pengalaman serupa bisa kita lihat pada tokoh Firdaus dalam Perempuan di Titik Nol (jadikan ini internal link ke artikelnya jika ada).
Dalam Q.S. An-Nisa (4): 1, manusia diseru untuk bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan mereka “dari diri yang satu” dan menjadikan pasangannya dari jenis yang sama. Namun, dalam praktik sosial, tafsir keagamaan yang bias gender sering menjadi alat politik untuk menundukkan perempuan.
Padahal, esensi Islam yang diwahyukan kepada Nabi berangkat dari semangat pembebasan, termasuk mengangkat derajat perempuan dari praktik jahiliyah. Karena itu, problem utamanya bukan “agama”, melainkan cara tafsir patriarkal dipakai sebagai legitimasi.
Sisterhood adalah Perlawanan
Meski pembaca disuguhi perjalanan yang memilukan, ada satu kekuatan yang muncul sebagai transformasi relasi antarperempuan. Mulanya, Mariam dan Laila ditempatkan dalam relasi kompetitif: istri tua dan istri muda. Akan tetapi, Hosseini mengubah dinamika itu menjadi bentuk solidaritas antarperempuan.
Ikatan emosional dan spiritual keduanya membangun kekuatan sisterhood. Konsep ini digagas bell hooks sebagai pilar gerakan perlawanan perempuan—yang berakar pada kasih sayang dan pengalaman yang sama.
Selain itu, penguasaan atas tubuh perempuan juga menjadi sorotan. Burqa, kehamilan, dan kekerasan tampil sebagai simbol bagaimana tubuh dijadikan alat kontrol.
Tafsir patriarkal
Hosseini tidak memposisikan Islam sebagai penyebab penindasan. Sebaliknya, ia mengkritik cara tafsir patriarkal bekerja sehingga Islam seolah membenarkan perempuan sebagai makhluk subordinat.
Pandangan ini sejalan dengan gagasan Amina Wadud dalam Qur’an and Woman (1999) yang menekankan pentingnya tafsir gender-sensitif. Dengan demikian, Mariam dan Laila dapat dibaca sebagai representasi perempuan Muslim yang tidak menolak identitas keagamaannya, tetapi menolak interpretasi yang menindas dengan dalih agama.
Dalam kecamuk rumah tangga yang penuh kekerasan, Mariam dan Laila menghidupkan ruang kecil untuk saling menguatkan. Ini membuktikan bahwa perlawanan perempuan tidak selalu lahir dari revolusi keras, melainkan juga dari cinta dan empati.
Solidaritas ini mengimplikasikan perlawanan simbolik terhadap sistem patriarki yang memecah-belah perempuan lewat rasa bersaing dan rasa bersalah.
Menurut Carol Gilligan, etika perempuan berakar pada care dan responsibility, bukan pada hukum rasional yang maskulin. Karena itu, pilihan pengorbanan Mariam dapat dibaca sebagai tindakan moral yang ia pegang dengan sadar. Keberanian, pada akhirnya, bisa lahir dari penderitaan yang dimaknai.
Matahari dari Langit Kabul
Penamaan A Thousand Splendid Suns terinspirasi dari puisi Persia Saib-e-Tabrizi yang memuji keindahan Kabul. Namun, dalam konteks novel ini, “a thousand splendid suns” menjadi metafora tentang perempuan Afghanistan yang tetap bersinar di tengah kehidupan yang berusaha menenggelamkan mereka.
Mariam yang sepanjang hidupnya diperlakukan layaknya aib justru menjadi sumber cahaya bagi Laila. Artinya, yang dianggap hina oleh sistem tidak otomatis kehilangan nilai. Dengan demikian, Hosseini menulis kisah menuju harapan dan rekonsiliasi kemanusiaan.
Novel ini memperlihatkan bahwa tubuh perempuan memiliki kekuatan regeneratif. Ia bukan hanya untuk melahirkan, tetapi juga untuk melahirkan makna dan peradaban baru.
Melalui A Thousand Splendid Suns, Hosseini menempatkan perempuan sebagai pusat sejarah. Mariam dan Laila adalah tokoh resiliensi sekaligus spiritualitas perempuan. Mereka bagian dari “seribu matahari yang gemilang”—sinar yang tak padam meski langit Kabul hancur oleh perang dan manusianya.
Pada akhirnya, pembaca diajak percaya bahwa dalam banyak kisah, kisah perempuan adalah kisah keberanian melawan keadaan yang selama ini ditulis oleh tangan laki-laki.
Bagikan artikel ini :

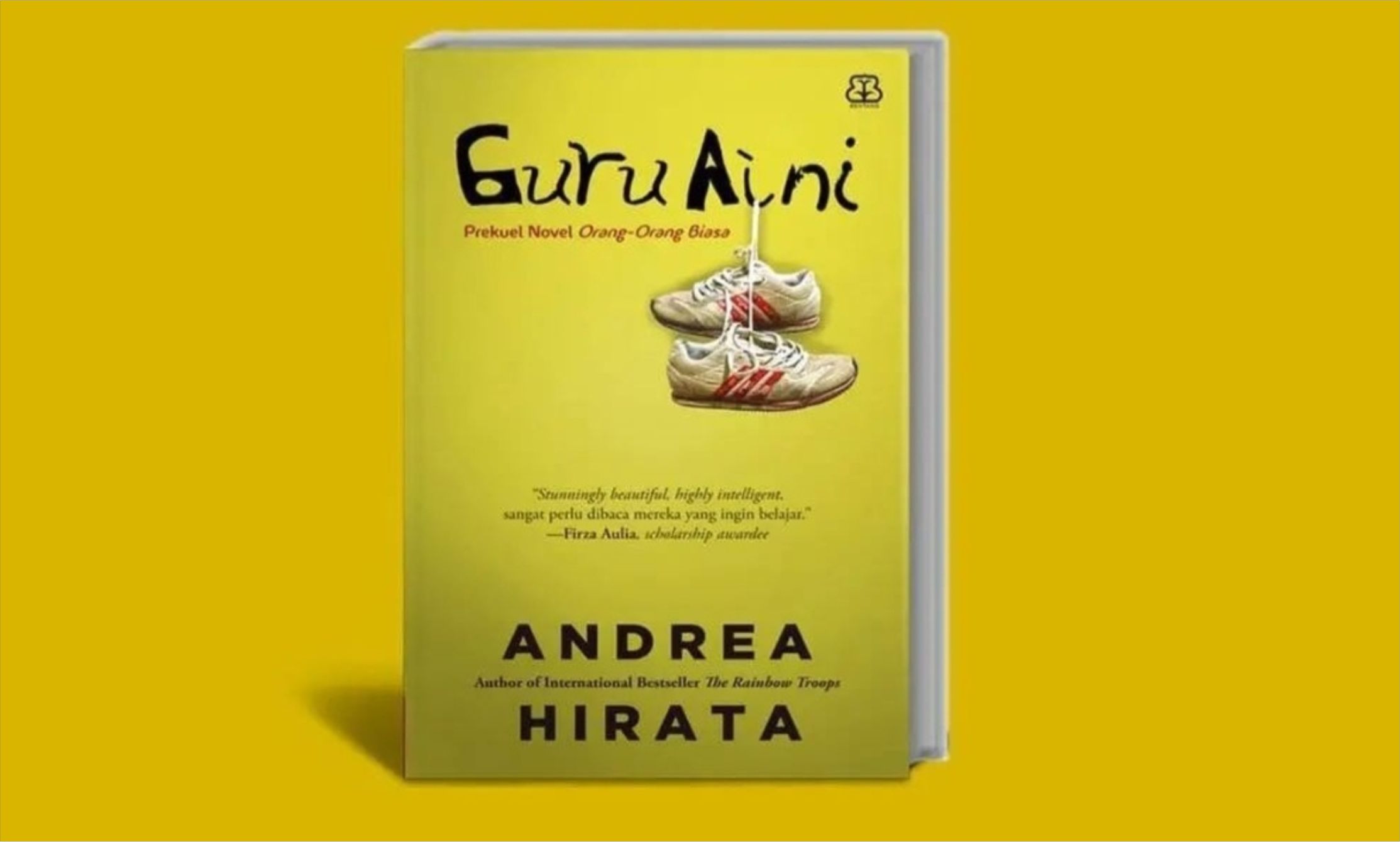












Post Comment